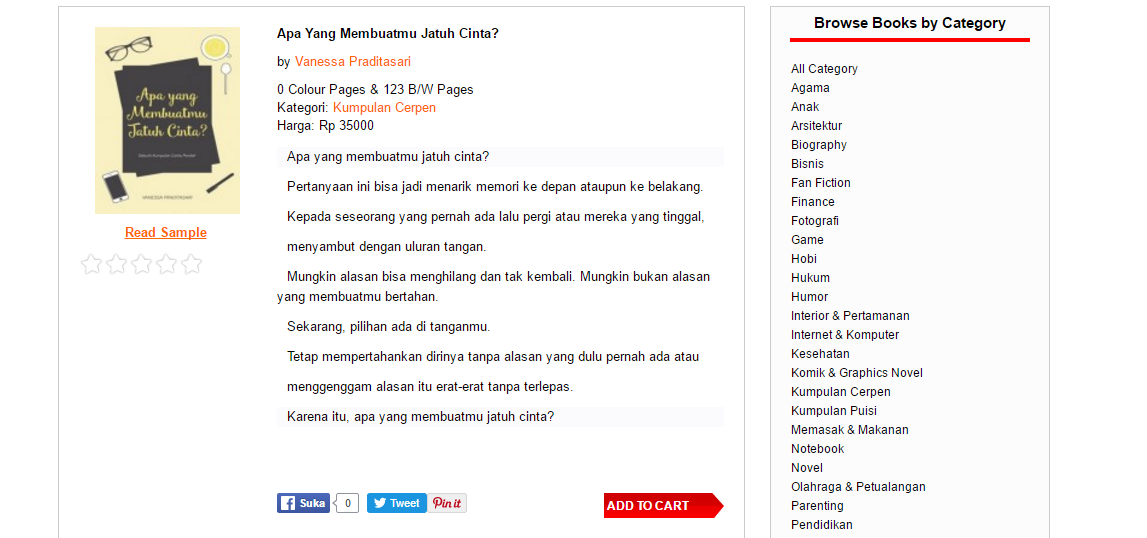Alasan pertama kami berada di kosnya
adalah lokasinya yang terdekat di antara kos kami dan alasan kedua adalah kamar
kosnya yang paling layak untuk diisi oleh tiga orang secara bersama-sama—total
empat dengan dirinya. Kamar yang ia tempati memang terhitung luas dibandingkan
dengan kamar kos pada umumnya, maklum kosan eksklusif yang dihuni para pemilik
roda empat.
Seorang satpam membukakan pintu
gerbang, menyapa ramah pemilik mobil dan menutup kembali pagarnya. Teman
kami—si penghuni kos, mengambil lahan parkir yang telah diberi kanopi dan papan
penanda dengan namanya, Ardian Tanusudibyo.
Bangunan kosnya berbentuk U,
dengan halaman parkir di tengah. Selain Ardian sudah ada dua mobil yang
menghuni masing-masing lahan parkir mereka dan masih ada lima lahan parkir lain
yang kosong. Dengan posisi lahan parkir seperti ini, setiap orang sebenarnya
bisa mengawasi mobil yang keluar masuk bahkan memastikan apakah penghuni kamar
tertentu sudah kembali ke kamar kos. Tapi siapa yang peduli, sudah ada satpam
yang menjaga di depan pagar 24 jam tanpa perlu khawatir ada kendaraan yang
hilang ataupun terjebak jam malam.
Kamar Ardian berada di lantai 2.
Tepat di sebelah tangga.
“Sorry ya, agak berantakan.”
Dia jelas berbasa-basi ketika
mengatakannya.
Ardian Tanusidbyo merupakan lelaki
yang paling tampan dan murah hati di antara dua lelaki yang bersamaku dalam
kelompok ini. Dan sebenarnya aku sempat merasa beruntung karena berada dalam satu
kelompok dengan Ardian yang terkenal sebagai pangeran kampus Ekonomi.
“Berantakan apanya Di? Kamar lu mending banget
dibanding kamar gue,” candaku sembari melepaskan sepatu di depan pintu.
Memasuki kamarnya yang begitu minimalis. Dalam arti yang sebenarnya.
Hanya sebuah kasur, kursi dan
meja yang dihuni oleh laptop, printer dan rak buku yang menempel di dinding.
Berderet-deret buku perkuliahan tersusun rapi, dari buku dengan ukuran terbesar
hingga terkecil. Di sebrang tempat tidur terdapat sebuah televisi yang menempel
di dinding dan sebuah rak tempel tempat Ardian menaruh gelas air minum bersama
beberapa makanan kecil.
Ardian menggelar karpet yang ia simpan di
sudut dinding. Menawarkan kami untuk duduk dan memulai apa yang harus kami
kerjakan. Tanpa banyak basa-basi Ardian membagi tugas dan secara tidak langsung
memaksa kami menyelesaikan pekerjaan kelompok seefektif mungkin. Tak ada
pembagian materi yang membuat sakit hati ataupun topik pembicaraan yang
mengalihkan inti berkumpulnya kami di sini.
Semua tugas selesai tepat ketika
azan magrib berkumandang. Ardi meminta ijin ke kamar mandi, meninggalkanku dan
dua orang lain—yang asik berdiskusi tentang sebuah game yang tak kumengerti. Sembari menunggu, kuperhatikan isi kamar
Ardian yang benar-benar tak banyak, kuamati potret keluarganya yang hanya
terdiri oleh ibu, ayah dan Ardian sendiri.
Ayahnya tampak seperti ayah yang
tegas, membentuk Ardian menjadi anak lelaki yang tampak sempurna dan ibunya
memiliki tatapan yang teduh, seperti penyeimbang di antara ketegasan dua lelaki
yang menatap kamera dengan tajam.
Kualihkan pandanganku ke rak buku
yang menempel di dinding. Sebagian besar adalah buku yang kukenal—buku
perkuliahan, yang jelas aku pun memilikinya. Sisa yang lain adalah novel-novel
dengan judul yang tak familiar.
Di antara semua buku tebal itu,
terselip sebuah buku tulis yang tak biasa. Tak berada di urutan yang tepat,
diapit oleh dua buku materi perkuliahan. Tanganku tergelitik untuk menarik buku itu
dari tempatnya. Membuka halaman pertamanya yang bertuliskan.
“Diary?”
“Saras?”
Suara Ardian mengusik fokusku
dari buku yang terbentang di atas tangan. Terbuka lebar pada halaman pertama,
mengundang senyuman dan gelengan kepalanya.
Tangan Ardian meraih buku yang
berada di tanganku. Menutupnya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Masih
dengan senyuman, ia pandangi rak buku itu sekali lagi dan berpaling. “Kalian
mau makan dulu atau langsung aku antar ke kampus?”
“Boleh sih kalau mau makan dulu.”
“Ngikut aja deh. Lu gimana Ras?”
“Eh—“ terkejut, kukembalikan
fokusku kepada dua orang teman yang menunggu jawaban. “Boleh sih. Gue laper,”
ujarku kemudian sambil tertawa hambar. Mataku berusaha menangkap ekspresi
Ardian, sepertinya aku sudah berbuat lancang dengan menyentuh ruang pribadinya,
haruskah aku meminta maaf atau—.
“Ya udah kalau gitu. Makan dulu.”
Kuanggukkan kepala mengikuti
langkah Ardian yang sudah didahului dua temanku yang lain. Sekedar memastikan,
kupanggil namanya. Hendak kuucapkan kata maaf sebelum ia bertanya,” Lu mau
makan apa Ras?”
“Ah—apa aja boleh sih.”
“Yang searah kampus aja Di, biar
nggak kejauhan balik kampusnya.”
“Lagian udah magrib juga,
sekarang kan kampus ada jam malamnya segala.”
“Eh, sejak kapan?” tanyaku
kemudian. Kulupakan niatku untuk meminta maaf, cara Ardian mengalihkan topik
seolah tidak ingin membahasnya. Kuanggap saja tidak terjadi apa-apa toh—aku
belum membaca apapun.
“Sejak kasus pembunuhan berantai
itu, lu seriusan nggak tau Ras?”
Kugelengkan kepala. “Berantai?
Sejak kapan kok berantai?”
“Sejak tiga bulan lalu. Korbannya
anak kampus kita, polanya sama. Katanya sih kalau sesuai urutan kampus, bulan
depan anak fakultas—“
“Ekonomi.”
Ardian memotong pembicaraan kami
tepat ketika ia menutup pintu mobil. “Kalau dari pintu masuk kampus, fakultas Hukum, FISIP, Psikologi, Ekonomi—“ dia menekan
tombol start engine dan mengatus suhu
pendingin sebelum menekan pedal gas,”katanya sih gitu.”
“Serius? Kok serem.”
“Makanya jam 10 malam satpam
kampus ngeronda muterin kampus. Mastiin nggak ada lagi mahasiswa setelah jam
segitu.”
“Ah—“ kuanggukkan kepala ragu,
entah perasaanku saja atau memang Ardian sempat melirikku dari spion dalam
ketika hendak berbelok keluar dari kawasan kosnya.
Setelah itu tak ada pembicaraan
lagi tentang pembunuhan berantai yang terjadi di kampus kami. Presentasi yang
akan dimulai di bulan berikutnya lebih menjadi topik utama pembicaraan, tapi
entah bagaimana topik itu menarik rasa penasaran membuatku mencari tahu berita
tentang pembunuhan berantai itu di malam setelah kepulanganku dari kos Ardian.
Hari demi hari berlalu berita
yang kubaca di malam itu hanya menjadi memori. Menginjak hari pertama bulan
September terjadi sedikit masalah yang membuatku kembali lagi ke kos Ardian
setelah terakhir kali dan pertama kali
kami mengerjakan tugas kami bersama.
Kamarnya masih tampak sama, tak
ada yang berubah. Ketika Ardian hendak mengambil laptopnya dari atas meja dan
membereskan kopian tugas yang harus kami kumpulkan, ponselnya berbunyi nyaring.
Sejenak ia melihat nama penelponnya sebelum memintaku mempersiapkan semuanya untuk
presentasi, terburu-buru Ardian keluar dari kamarnya untuk menjawab telepon.
Laptop sudah kumasukkan.
Kertas-kertas di atas meja pun sudah kusiapkan dalam map. Ardian tak kunjung
kembali, tak ada pula di beranda lantai dua ketika kulongokkan kepala melewati
pintu. Kuputuskan untuk menunggu di dalam kamar dan memerhatikan kembali potret
keluarganya, lalu rak buku, termasuk buku tulis yang masih tampak ganjil di
antara buku-buku lainnya.
Rasa penasaran menggelitik,
tentang bagaimana isi buku diary
seorang anak cowok. Apakah sama dengan diary
anak cewek yang penuh dengan kisah cinta dan perasaan mereka atau bagaimana—dan
ini diary seorang Ardian, lelaki yang
tampak begitu sempurna.
Jariku menarik buku tulis itu
keluar dari rak. Membuka halaman pertamanya. Halaman keduanya lalu halaman
ketiganya yang kosong. Dahiku mengkerut, kutempelkan ibu jari di sisi buku dan
kulepaskan dengan cepat hingga tampak halaman yang berisi tulisan.
Kubaca isinya dengan sebuah judul
nama di atasnya.
Thalia Dara G. Fakultas FISIP.
Kartu perpustakaan seorang
perempuan berkulit sawo matang dengan rambut sebahu tertempel di sana. Dahiku
mengkerut memastikan nama yang terdengar familiar. Tapi siapa, aku tak merasa
mengenal seseorang dari jurusan FISIP.
Halaman selanjutnya bertuliskan
nama lain.
Yunita Chandra. Fakultas
Psikologi.
Kali ini kartu mahasiswa yang
tertempel di halaman buku, dari fotonya tampak seorang perempuan berjilbab yang
mengenakan kacamata. Bukan wajah yang familiar tapi nama ini begitu familiar.
Entah bagaimana begitu familiar.
Kubalik halaman-halaman
sebelumnya. Tampak sebuah nama lain dari Fakultas Hukum. Sebuah kartu
perpustakaan kembali tertempel di halaman.
Aku berusaha mengingat siapa
orang-orang ini.
Korban pertama Fakultas Hukum, kedua Fakultas FISIP, ketiga Psikologi.
Thalia Dara G, Yunita Chandra. Selalu ada identitas korban yang raib, sehingga
polisi menyimpulkannya sebagai—
“Menurut kamu gimana Ras?”
Buku di tanganku terjatuh,
kubalikkan badan. Kurasakan dingin menyergap hingga tanganku gemetar, ketika sosok
Ardian berdiri tepat di hadapanku. Secara tiba-tiba dadaku sesak, kamar kosnya
yang kukira luas terasa menyempit, mengecil, hingga membuatku seolah tersudut,
ciut.
Ardian tersenyum, seperti
senyuman ketika aku menemukan buku itu pertama kali. Ataupun senyuman ketika
mengembalikan buku itu ketempatnya. Senyuman yang seolah memberitahuku apa yang
akan diperbuatnya.